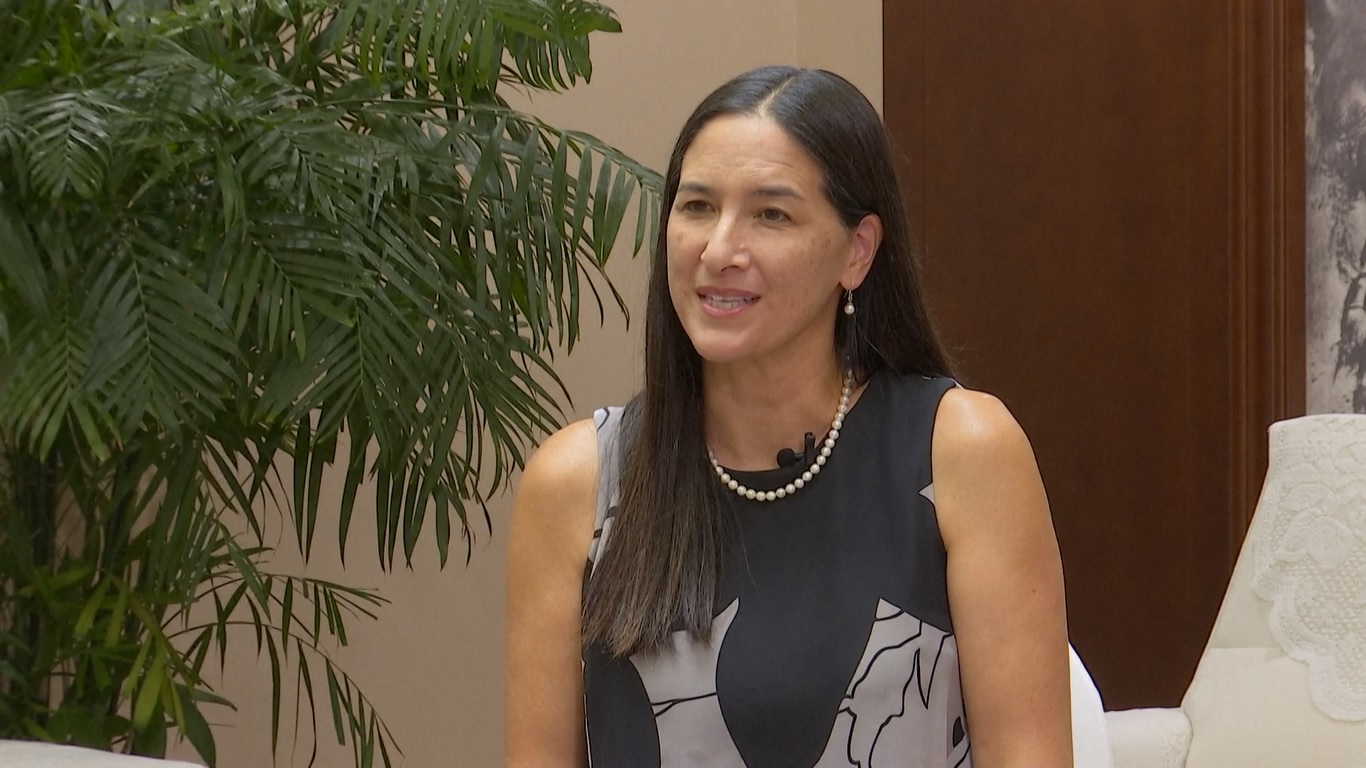Rilis film dokumenter “Guardians of Civilization: Relocating China’s National Treasures” oleh China Global Television Network (CGTN) menyajikan kisah luar biasa tentang bagaimana Tiongkok menjaga denyut peradabannya di tengah kengerian Perang Dunia II.
Dokumenter berdurasi tujuh menit ini bukan sekadar arsip visual; ia menghadirkan kembali salah satu operasi perlindungan budaya terbesar dan terpanjang dalam sejarah manusia. Ketika Jepang menduduki Shanhaiguan pada Januari 1933, pihak Museum Istana di Beijing sadar bahwa kekalahan militer bukanlah satu-satunya ancaman.
Lebih dari itu, identitas bangsa, yang terwujud dalam artefak budaya, juga berada di ujung tanduk. Dari sinilah keputusan monumental dibuat untuk memindahkan koleksi perunggu, porselen, lukisan, dan batu giok ke wilayah selatan dan barat daya Tiongkok, menempuh perjalanan berliku sejauh lebih dari 6.000 kilometer dalam kurun waktu 14 tahun.
Operasi ini berhasil membawa lebih dari 13.400 peti harta karun nasional akhirnya tiba kembali di Nanjing pada tahun 1947 dengan kerusakan yang hampir nihil. Hal ini menunjukkan sebuah fakta penting bahwa di tengah perang, negara bisa menempatkan kebudayaan sebagai prioritas setara dengan nyawa dan wilayah.
Jika dilihat dengan lensa teori hubungan internasional, keputusan ini tidak hanya bersifat kultural, melainkan juga strategis. Dari perspektif realisme, biasanya perhatian terpusat pada kekuatan militer, senjata, dan strategi bertahan hidup negara.
Namun, pengalaman Tiongkok memperlihatkan dimensi lain dari survival, yaitu melindungi simbol peradaban sebagai fondasi legitimasi dan moral nasional. Karena bagi Tiongkok, artefak budaya bukan sekadar barang antik melankan “urat nadi peradaban” yang meneguhkan semangat rakyat di tengah keterpurukan.
Jika menggunakan pendekatan konstruktivisme, yang menekankan pentingnya ide, identitas, dan norma, maka evakuasi besar-besaran ini justru menjadi tindakan “pembentukan makna.” Para kurator dan birokrat museum mengartikulasikan bahwa menjaga benda budaya sama pentingnya dengan mempertahankan dokumen kenegaraan.
Dengan kata lain, identitas bangsa tidak boleh lenyap walau negara dalam kondisi terjepit. Tidak mengherankan bila dekade setelahnya banyak seniman Tiongkok menciptakan lukisan dan catatan untuk mengenang perjalanan bersejarah ini. Ingatan kolektif tersebut terus diperbarui hingga hari ini, termasuk lewat film dokumenter CGTN, yang sekaligus memperkuat narasi bahwa museum bukan gudang barang mati, melainkan institusi memori bangsa.
Pengalaman ini juga dapat dibaca dari perspektif English School, yang melihat bagaimana negara-negara membentuk masyarakat internasional dengan norma bersama. Tragedi penjarahan dan penghancuran warisan budaya selama Perang Dunia II, termasuk pengalaman Tiongkok, mendorong lahirnya Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata.
Konvensi ini, yang kini diratifikasi lebih dari 130 negara, menandai pergeseran norma global bahwa warisan budaya dianggap bukan hanya milik nasional, melainkan juga bagian dari warisan umat manusia. Mekanisme tanda pengenal Blue Shield, perlindungan khusus, dan kerja sama internasional adalah institusionalisasi nilai bahwa peradaban tidak boleh musnah karena perang.
Namun, institusi global hanya efektif jika negara memiliki kapasitas domestik. Dari perspektif liberal institusionalis, keberhasilan evakuasi Tiongkok adalah hasil tata kelola yang rapi seperti pengemasan yang memakan waktu setahun, koordinasi antarlembaga, pencatatan detail, hingga pengaturan rute aman.
Inilah contoh nyata bagaimana kapasitas institusional menentukan keberhasilan perlindungan budaya. Kegagalan koordinasi bisa berakibat fatal, sebagaimana kasus penjarahan Museum Nasional Irak tahun 2003.
Sebaliknya, pengalaman Ukraina pada masa invasi Rusia menunjukkan bahwa ketika negara, masyarakat sipil, dan mitra internasional berkolaborasi, ribuan artefak bisa diselamatkan dari kehancuran. Dengan kata lain, perlindungan warisan budaya di masa konflik bukan sekadar soal niat, tetapi juga soal kesiapan institusi dan jaringan kerja sama.
Selain itu, teori sekuritisasi dari Copenhagen School juga relevan. Para pengelola museum dan pemerintah Tiongkok berhasil “mendeklarasikan” warisan budaya sebagai isu eksistensial. Begitu publik diyakinkan bahwa benda-benda ini adalah inti identitas bangsa, maka pengorbanan biaya, tenaga, dan risiko untuk evakuasi menjadi sah dan diterima.
Inilah yang memungkinkan operasi besar itu berjalan dengan dukungan luas. Mekanisme serupa kini banyak digunakan di berbagai konflik modern, dari Suriah hingga Ukraina, di mana situs budaya dijadikan simbol perlawanan dan alasan mobilisasi internasional.
Hasil jangka panjang dari strategi ini adalah akumulasi soft power. Koleksi yang selamat menjadi bukti ketahanan peradaban Tiongkok, yang kemudian dipamerkan secara global, memperluas pengaruh tanpa paksaan. Ia menjadi alat diplomasi budaya yang efektif, memperkuat narasi Tiongkok sebagai peradaban tua yang mampu menjaga kontinuitas sejarahnya.
Bahkan, dinamika bahwa sebagian koleksi kini disimpan di National Palace Museum di Taipei juga membuka bab diplomasi budaya lintas Selat Taiwan. Artefak yang dulu berjalan bersama kini berfungsi sebagai “diplomat senyap,” yang kadang menyatukan, kadang menegangkan hubungan, tetapi selalu mengingatkan pada akar budaya yang sama.
Dari sisi kebijakan, ada beberapa pelajaran penting untuk masa kini. Pertama, persiapan pra-krisis harus dilakukan dengan serius. Inventarisasi digital, sistem pengemasan standar, dan rencana evakuasi darurat perlu tersedia sebelum konflik pecah.
Kedua, perlindungan warisan budaya tidak bisa dilepaskan dari arsitektur hukum internasional. Ratifikasi Konvensi Den Haag dan penerapan protokolnya di level domestik menjadi keharusan, termasuk koordinasi antara kementerian budaya, pertahanan, dan aparat lokal.
Ketiga, komunikasi publik harus dikelola dengan baik. Dukungan masyarakat hanya bisa diperoleh jika mereka memahami bahwa benda budaya bukan sekadar barang kuno, melainkan identitas dan memori bersama yang layak diperjuangkan.
Dengan demikian, kisah evakuasi lebih dari 13 ribu peti harta karun Museum Istana bukan sekadar peristiwa sejarah. Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memahami dirinya, melindungi identitasnya, dan membangun legitimasi moral di tengah bencana perang.
Dari perspektif realis, konstruktivis, English School, liberal, hingga teori sekuritisasi, semuanya sepakat bahwa perlindungan warisan budaya adalah indikator kedewasaan strategis sebuah negara. Dokumenter singkat CGTN ini berhasil merangkum pesan besar itu bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari tank dan senjata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga memori dan peradaban.