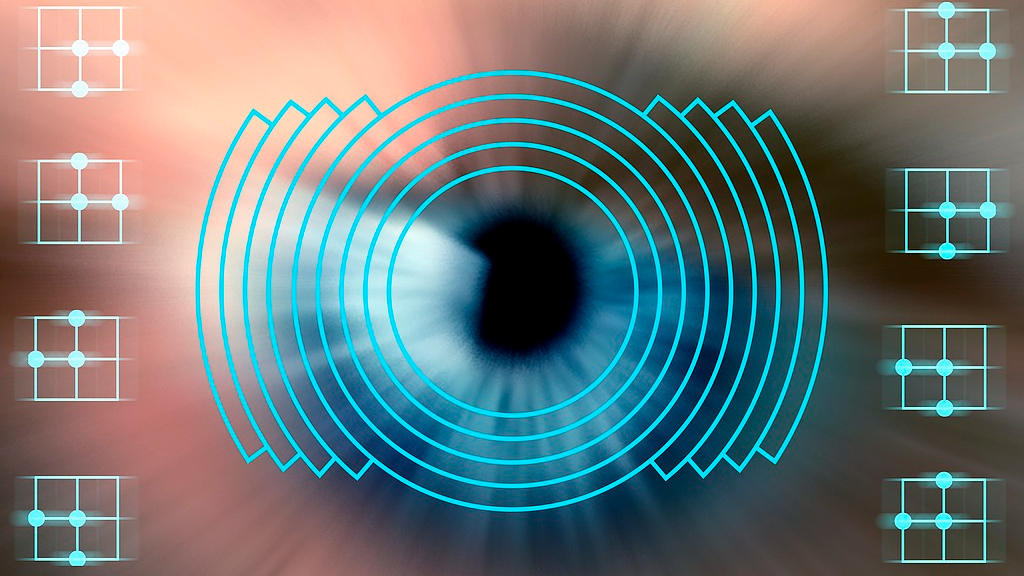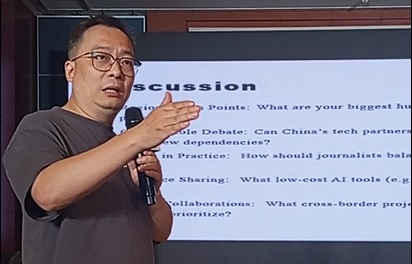Di tengah perubahan zaman yang ditandai oleh krisis iklim, ledakan populasi, dan perlombaan inovasi teknologi, Tiongkok tampil sebagai aktor global yang semakin kompleks. Negara ini tidak lagi hanya memamerkan kekuatan ekonominya atau menunjukkan keperkasaannya melalui proyek-proyek infrastruktur berskala besar.
Alih-alih, Beijing justru kini memadukan teknologi canggih dengan elemen-elemen budaya, sains, dan kebijakan luar negeri menjadi satu strategi besar dengan tujuan untuk membangun pengaruh global secara halus tapi sistematis.
Salah satu contoh menarik adalah integrasi antara kecerdasan buatan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Inovasi ini bukan hanya membawa kemajuan medis, tetapi juga menjadi instrumen baru dalam diplomasi kesehatan dan perluasan soft power Tiongkok.
Perangkat diagnostik berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan di Hangzhou kini mampu meniru metode empat langkah diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok yaitu melihat, mendengar, bertanya, dan merasakan.
Kolaborasi antara Universitas Zhejiang Shuren dan Congbao Technology telah menghasilkan alat yang tak hanya objektif dalam menganalisis kondisi pasien, tetapi juga menyimpan data dalam skala besar untuk personalisasi pengobatan.
Bagi masyarakat luar negeri yang selama ini memandang pengobatan tradisional Tiongkok dengan skeptis karena dianggap tidak ilmiah atau berbasis mistik, maka setidaknya pendekatan berbasis data ini membuka pintu pemahaman baru.
Kecerdasan buatan menjadi penerjemah budaya, membuat pengobatan tradisional Tiongkok lebih mudah dipahami dan diterima. Di Belarus, misalnya, teknologi ini mulai diterapkan di rumah sakit nasional dengan respons publik yang sangat positif. Dengan begitu, Tiongkok sedang membangun kembali citra warisan budayanya menjadi sesuatu yang modern, bermanfaat, dan global.
Dari perspektif teori hubungan internasional, strategi ini bisa dibaca dalam kerangka soft power ala Joseph Nye, yaitu bagaimana suatu negara memengaruhi pihak lain bukan dengan paksaan atau uang, tetapi dengan daya tarik nilai, budaya, dan model pembangunan.
Sementara dari kacamata konstruktivisme, Tiongkok sedang mengonstruksi ulang makna dari identitas budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan yang tradisional dan futuristik demi membentuk norma baru dalam tatanan dunia.
Namun Tiongkok tidak berhenti di situ. Inovasi teknologi yang dikembangkan negeri ini juga menjawab masalah global lain, yaitu krisis lingkungan akibat limbah plastik. Kolaborasi ilmuwan dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa berhasil menciptakan teknologi daur ulang yang mengubah sampah plastik menjadi bensin dan bahan kimia industri hanya dalam satu langkah, tanpa energi tinggi dan tanpa proses deklorinasi yang kompleks. Hasilnya, bahkan plastik berbahaya seperti polivinil klorida bisa diubah menjadi sumber energi, dengan efisiensi konversi hingga 99 persen.
Teknologi ini, selain menjadi solusi potensial untuk masalah pencemaran plastik global, juga membuka pertanyaan serius tentang keadilan teknologi. Apakah inovasi seperti ini akan tersedia luas untuk negara-negara berkembang yang saat ini menjadi tempat penampungan sampah dunia? Ataukah ia akan dimonopoli oleh negara maju sebagai sumber daya strategis baru?
Dari sudut pandang geopolitik, inovasi ini juga menjadi cermin bagaimana negara-negara besar menggunakan teknologi lingkungan sebagai alat pengaruh. Jika Tiongkok membuka akses teknologi ini, ia dapat memperkuat posisi diplomatiknya di kawasan Global South.
Namun jika sebaliknya, teknologi ini bisa menjadi alat hegemoni baru. Pendekatan ini sejajar dengan strategi “vaksin diplomasi” Tiongkok selama pandemi COVID-19, di mana distribusi vaksin ke negara-negara berkembang memperluas jaringan pengaruh luar negeri Beijing.
Dalam konteks yang lebih luas, Tiongkok juga menunjukkan langkah strategis dalam ranah teknologi robotika. Konferensi Robot Dunia dan Permainan Robot Humanoid Dunia 2025 menjadi panggung besar untuk memperlihatkan bagaimana robot humanoid kini sudah hadir dalam kehidupan nyata. Dari manufaktur, rumah tangga, pertanian, hingga olahraga, lebih dari 500 robot humanoid dari 16 negara bersaing dan menunjukkan otonomi tinggi dalam berbagai tugas, tanpa kendali jarak jauh.
Di sinilah terlihat dengan jelas pendekatan “developmental state” Tiongkok yang khas. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator atau pemberi dana, tetapi menjadi arsitek ekosistem inovasi yang terintegrasi baik dari riset, regulasi, pasar, hingga budaya.
Robot yang diperkenalkan bahkan tampil dengan sentuhan tradisi seperti kungfu dan opera Tiongkok, membentuk narasi bahwa modernitas tidak harus identik dengan Barat. Makanya, konsep seperti “sociotechnical imaginaries” dalam kajian Science & Technology Studies menggambarkan bahwa Tiongkok tengah membangun imajinasi kolektif tentang masa depan di mana teknologi menjadi bagian dari identitas nasional dan diplomasi budaya.
Hal ini bertolak belakang dengan pendekatan negara-negara Barat, yang cenderung menyerahkan inovasi kepada sektor swasta dan hasilnya sering terfragmentasi. Mungkin, inilah yang membuat inovasi Tiongkok bisa lebih cepat dari Barat.
Namun, strategi ini juga menghadapi tantangan. Persaingan standar internasional, ketergantungan pada komponen canggih, hingga risiko pengangguran akibat otomatisasi adalah isu-isu yang tak bisa dihindari. Negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa mengambil pelajaran dari sini, bahwa membangun kapasitas inovasi nasional perlu orkestra kebijakan, bukan sekadar insentif jangka pendek.
Inovasi yang mungkin paling strategis adalah GEAIR, robot pertanian kecerdasan buatan pertama yang mampu melakukan pemuliaan tanaman secara mandiri. Robot ini dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan menjadi simbol dari pergeseran paradigma pertanian global. Ketika krisis iklim, degradasi lahan, dan disrupsi pasokan pangan menjadi realitas, pertanian presisi menjadi solusi strategis untuk menjamin ketahanan pangan.
GEAIR mampu mengidentifikasi bunga, melakukan penyerbukan silang, dan menyelesaikan proses pemuliaan secara otomatis, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara manual dengan waktu dan biaya yang tinggi.
Dari perspektif realisme struktural, teknologi seperti ini bukan sekadar alat produksi, melainkan instrumen kekuasaan dan kedaulatan pangan. Dari sudut pandang neo-merkantilisme, ia menjadi alat ekspansi pengaruh ke negara-negara berkembang yang tertarik mengadopsi teknologi ini sebagai bagian dari kerja sama pembangunan.
Di sinilah Tiongkok menunjukkan bahwa penguasaan teknologi bukan hanya soal paten atau pabrik, melainkan tentang siapa yang bisa menawarkan solusi terhadap kebutuhan mendesak umat manusia seperti kesehatan, energi, pangan, dan lingkungan.
Terakhir, hadirnya drone laut “Albatross” memperluas cakupan pengaruh Tiongkok hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau seperti samudra. Wahana laut tanpa awak ini mampu memasuki pusat badai tropis dan mengumpulkan data penting tentang formasi topan. Dengan sistem navigasi otonom dan sensor canggih, Albatross menawarkan revolusi dalam prakiraan cuaca dan mitigasi bencana.
Namun di balik manfaat ilmiahnya, ada kepentingan strategis yang mengintai. Dalam hubungan internasional, informasi adalah kekuasaan. Negara yang menguasai data tentang laut dan atmosfer dapat mengontrol jalur pelayaran, menentukan kebijakan iklim, bahkan membangun dominasi maritim baru.
Dari perspektif realisme, proyek seperti Albatross adalah bagian dari upaya Tiongkok mengokohkan pengaruhnya di wilayah perairan strategis, termasuk Laut Cina Selatan. Sebaliknya, pendekatan liberal menawarkan potensi kolaborasi global jika data ini dibagikan secara terbuka untuk kepentingan bersama.
Teknologi seperti ini mencerminkan kaburnya batas antara sains dan strategi. Lautan kini bukan lagi hanya arena perdagangan, tapi juga medan kontestasi data dan pengaruh. Dalam dunia yang makin bergantung pada informasi dan sensor, wahana laut seperti Albatross bisa menjadi peta kekuasaan baru.
Apa yang dilakukan Tiongkok hari ini menunjukkan bahwa kekuatan global tidak lagi semata ditentukan oleh militer atau ekonomi makro. Negara yang mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam budaya, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan diplomasi akan memenangkan masa depan.
Soft power kini tidak hanya berarti film dan musik, tetapi juga solusi konkret terhadap persoalan global yang ditawarkan melalui teknologi. Bagi negara-negara berkembang, ini bisa menjadi inspirasi sekaligus peringatan. Mereka perlu bertanya, apakah akan menjadi pengguna pasif dari teknologi asing, ataukah akan mulai membangun narasi dan inovasi sendiri yang berakar pada kebutuhan lokal dan kekayaan budaya nasional?
Karena di abad ke-21, pengaruh suatu negara mungkin tidak lagi ditentukan oleh berapa banyak senjata yang dimilikinya, tetapi oleh berapa banyak solusi yang bisa ditawarkannya kepada dunia. Dan setidaknya, apa yang telah dilakukan Tiongkok hari ini telah membuktikan hal tersebut.